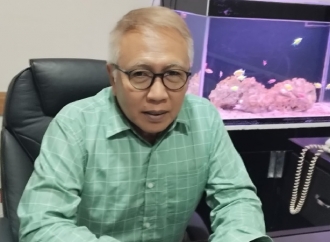Politik "Cawe-cawe" Soeharto dan Jokowi -Penyerangan Bukan Kerusuhan -Jumlah Korban dan Kegagalan Negara -Investor Asing dan Donor Luar Negeri di Balik Represi Orde Baru -Kilas Balik Gus Dur dan Megawati Melawan Soeharto -Ketakutan Soeharto pada Megawati -Kudatuli sebagai Tonggak Reformasi -Jokowi Si Malin Kundang: Soerjadi atau Soeharto?
Jakarta, Gesuri.id - Tragedi penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 adalah fakta sejarah tentang politik "cawe-cawe" Soeharto dan Orde Baru dalam bentuknya yang paling brutal terhadap partai politik dan kelompok oposisi pro demokrasi yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.
Ironisnya, meskipun Soeharto dan Orde Baru telah jatuh, hingga saat ini, Peristiwa 27 Juli 1996 belum diakui oleh Negara sebagai pelanggaran HAM berat. Padahal sudah banyak tuntutan dan penyelidikan selama bertahun-tahun. Peringatan 27 Juli tahun 2024 akan terhitung 28 tahun.
Karena itu bukan hal yang aneh kalau politik "cawe-cawe" masih dilanjutkan Jokowi. Istilah "cawe-cawe" muncul dari mulut Jokowi sendiri.
Bagaimana Pemerintah mau jera dan "bertaubat" melakukan "cawe-cawe", kalau pelanggaran HAM berat dari Peristiwa 27 Juli 1996 saja tidak diakui dan ditindak secara serius?
Modus operandi dari politik "cawe-cawe" akan terus berulang di panggung kekuasaan. Bedanya kalau dulu menggunakan aparat dengan kedok preman jalanan, saat ini dalam bentuk mafia pembegalan konstitusi dan perundang-undangan.
Bukan Kerusuhan dan Tapi Penyerangan
Tragedi 27 Juli 1996 dikenal dengan sebutan "KUDATULI" singkatan dari Kerusuhan 27 Juli atau dikenal juga dengan "Peristiwa Sabtu Kelabu", karena hari kejadian 27 Juli 1996 adalah hari Sabtu.

Sebenarnya istilah "kerusuhan" tidak tepat, bahkan menyesatkan. Karena fakta yang terjadi adalah penyerangan dan pemaksaan dengan kekerasan yang berdampak pada pembunuhan, luka-luka, penghilangan orang dan kerusakan lainnya yang diduga telah direncanakan secara sistematis, artinya tidak bisa disebut dengan istilah kerusuhan yang biasanya terjadi acak dan sporadis.
Sabtu 27 Juli 1996 itu, "massa" yang disebut-sebut sebagai pendukung Soerjadi (Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan Juni 1996 yang didesain oleh rejim Orde Baru) yang direstui oleh Presiden Soeharto dan diterima di Istana Negara pada tanggal 25 Juli 1996 menyerang kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro yang dijaga oleh pendukung Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri (hasil Kongres Surabaya 1993).
Melalui rekonstruksi peristiwa berdasarkan laporan dan investigasi Komnas HAM dan Tim Ivestigasi lainnya, juga laporan media massa dan hasil penelitian akademis bahwa "massa" penyerang adalah pasukan berpostur tegap dan berambut cepak yang "berkaos merah PDI" yang tampak terlatih, diangkut dengan truk-truk mulai dan diturunkan di titik-titik sekitar kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro mulai pukul 05.00 pagi. Jumlah dari pasukan itu terus bertambah hingga sekitar 500 orang dan pada pukul 06.15 mulai menyerang dengan lemparan batu ke arah dalam gedung dan mulai menyerang masuk.
Sedangkan aparat kemanan malah menutup akses-akses jalan menuju kantor DPP PDI sehingga pasukan itu dengan bebas menyerang kantor PDI sementara massa yang mulai berdatangan yang niatnya membantu korban yang ada di dalam kantor PDI tidak bisa masuk karena dihambat dan ditutup aksesnya oleh aparat keamanan.
Jumlah Korban
Berdasarkan Laporan Komnas HAM waktu itu, yang sehari setelah kejadian melakukan investigasi, di bawah pimpinan Asmara Nababan dan Baharuddin Lopa, menyebut jumlah korban: ada 5 (lima) orang tewas, 149 orang luka, 23 orang hilang dan 136 orang ditangkap (per Agustus). Adapun kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 100 miliar akibat dari peristiwa keji tersebut.
Komnas HAM waktu itu juga telah menilai terjadi 6 (enam) bentuk pelanggaran HAM: pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat, pelanggaran asas kebebasan dari rasa takut, pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi, dan pelanggaran perlindungan terhadap jiwa manusia, juga pelanggaran asas perlindungan atas harta benda.
Laporan Komnas HAM saat itu juga telah menyimpulkan adanya indikasi terjadinya pelanggaran HAM yang berat.
Sementara menurut laporan Amnesty Internasional pada 30 Juli 1996 menemukan 5-7 orang tewas, 90 orang luka-luka, 206-241 orang ditangkap, dan pembatasan informasi oleh aparat yang menghambat pemantau HAM saat berupaya memastikan jumlah kematian.
Sekali lagi: meskipun fakta dan bukti sudah terang-benderang tapi hingga saat ini Negara belum mau mengakui Tragedi 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran HAM berat.
Negara Gagal
Menurut Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (20 Juli 2024) hal itu menunjukkan ketidakmampuan dan kegagalan Negara menegakkan HAM atas Tragedi 27 Juli 1996, artinya Negara masih menolak Peristiwa "Kudatuli" sebagai pelanggaran HAM berat dan enggan menyelesaikan secara adil. Dan Komnas HAM sendiri tidak melakukan penyelidikan projustisia atas peristiwa tersebut.
Buktinya, masih menurut Usman Hamid, Negara hanya menggelar "Pengadilan Konektivitas: yang merupakan pengadilan pidana biasa yang memakai aturan terkait kejahatan biasa dan bukan kejahatan luar biasa (pelanggaran HAM).
Dan hasil Pengadilan itu pun mudah ditebak, hanya bisa memvonis dari pihak sipil: Jonathan Marpaung yang terbukti mengerahkan massa dan melempar batu ke kantor DPP PDI dengan dijatuhi hukuman hanya 2 bulan 10 hari.
Sedangkan dua perwira militer yang disidang: Budi Purnama dan Suharto divonis bebas.
Padahal sudah jelas-jelas ada korban yang tewas 5 orang (versi Komnas HAM) dan 5-7 orang (versi Amnesty International) serta ratusan lainnya luka-luka, puluhan orang hilang dan ditangkap tanpa proses pengadilan.
Tuntutan agar Peristiwa 27 Juli 1996 diakui sebagai pelanggaran HAM berat terus menggema.
Tahun lalu, dalam "Diskusi Publik Komnas HAM", 28 Juli 2023, Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM periode 2007-2012 telah menegaskan Peristiwa 27 Juli 1996 sudah memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Jika dibaca dalam konteks Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000 dan konteks hukum pidana internasional, Tragedi 27 Juli 1996 sudah termasuk dalam kejahatan kemanusiaan.
Demi Investor Asing dan Donor Luar Negeri
Mengapa Peristiwa 27 Juli 1996 menemui hambatan dan kesulitan saat dibongkar? Karena peristiwa itu bukan kejahatan biasa, tapi melibatkan aktor-aktor dari Negara dan Pemerintah yang berkuasa saat itu.
Penyerangan Kantor DPP PDI 27 Juli 1996 merupakan usaha represif yang dilakukan oleh aktor-aktor Negara dan Pemerintah saat itu yang dipimpin Soeharto untuk membungkam kelompok-kelompok Oposisi dan Pro Demokrasi.
Peristiwa 27 Juli 1996 tidak bisa dilepaskan dari konteks politik saat itu, Orde Baru dan Soeharto sedang gencar melakukan konsolidasi kekuatan guna menghadapi Pemilu 1997.
Orde Baru dan Soeharto pun melalukan "cawe-cawe" dalam bentuknya yang paling brutal dengan memaksa menghancurkan aktor-aktor dan kelompok-kelompok oposisi.
Di mana bentuk brutalnya? Karena saya sependapat dengan pidato Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (20 Juli 2024) bahwa Penyerangan 27 Juli 1996 adalah "serangan terhadap peradaban demokrasi, serangan terhadap sistem hukum, serangan terhadap kemanusiaan dan serangan terhadap lambang kedaulatan partai berupa kantor partai."
Di balik gaya brutal Soeharto itu ada tujuan politik dan ekonomi demi kepentingan dia dan lingkaran kekuasaannya.
Dalam buku "Politik dan Ideologi Politik PDI Perjuangan (1987-1999)" yang disusun Djarot Saiful Hidayat dan Endi Haryono, Soeharto terobsesi mengembalikan kejayaan Golkar yang hilang suaranya 5 persen pada Pemilu 1992 dan berusaha keras mengonsolidasikan rejim Orde Baru.
Tujuannya dukungan yang mutlak pada rejim Orde Baru sehingga Soeharto percaya diri dalam meyakinkan investor asing serta keberlanjutan donor pembangunan luar negeri untuk Indonesia. Maka, segala macam cara dihalalkan guna meraih tujuan politik dan ekonomi itu.
(Sampai bagian ini ada yang 'dejavu' saat ini ada tokoh Mafia Politik yang berambisi menjadi presiden 3 periode, namun gagal, akhirnya digunakan segala cara mengkooptasi MK untuk meloloskan pecalonan anaknya, kemudian menantunya, melalui putusan MA meloloskan anak bungsunya, dengan alasan keberlangsungan proyek-proyek yang ia bangun, khususnya pembangunan IKN untuk menarik investor-investor asing?)
Kampanye Orde Baru: Anti-Mega dan Anti-Gus Dur
Selama era Orde Baru Soeharto melakukan gaya politik kolonial, politik pecah belah, politik adu domba, atau "divide et impera" untuk menghancurkan kelompok oposisi pro demokrasi.
Megawati Soekarnoputri yang terpilih sebagai Ketua Umum PDI melalui Kongres Surabaya tahun 1993 dianggap sebagai kekuatan oposisi terkuat menghadapi Soeharto pada Pemilu 1997.
Tidak hanya Megawati yang menjadi sasaran kelaliman Soeharto saat itu, nasib yang sama juga menimpa Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU.
Gus Dur yang terpilih sebagai Ketua Forum Demokrasi (Fordem) pada tahun 1991 dituding semakin kritis pada rejim Orde Baru.
Sebagai balasan, Orde Baru melancarkan konspirasi pendongkelan Gus Dur melalui Muktamar di Cipasung pada tahun 1994. Dimunculkan calon boneka: Abu Hasan. Namun upaya itu gagal total.
Tapi bukan berarti serangan berhenti, dimulailah politik pecah belah karena Abu Hasan yang didukung Orde Baru membentuk Pengurus PBNU tandingan dengan nama Pengurus Koordinasi Pusat NU (PKP NU) serta upaya menggugat ke pengadilan atas pengurus PBNU pimpinan Gus Dur.
Megawati juga bernasib serupa. Pengurus DPPnya dibelah, dibentuk pengurus boneka yang didukung rejim Orde Baru bernama Pengurus PDI Nasional sejak Desember 1994.
Tokoh dan kelompok PDI anti Megawati inilah atas dukungan penuh Orde Baru menggelar Kongres Medan Juni 1996 yang sepakat memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI untuk menggusur Megawati.
Menurut Greg Barton dalam "Biografi Gus Dur" sepanjang tahun 1995 dan memasuki tahun 1996, Gus Dur memang bekerja sama erat dengan Megawati (2003: 260).
Pasangan oposisi ini menakutkan bagi Soeharto. Sehingga dimulai fitnah dan pembunuhan karakter terhadap keduanya. Untuk melemahkan kredibilitas Megawati dengan menuduh pendukung-pendukungnya mempunyai hubungan dengan PKI. Gus Dur dituduh bukan muslim yang taat tapi pro Kristen. Dituduh agen Israel, Mossad dan agen Partai Sosialis Baath Iraq.
Apalagi Gus Dur dan Megawati mulai bisa mengambil hati anak-anak muda dan gerakan pro demokrasi, gelombang perlawanan terhadap Orde Baru makin membesar.
Tapi yang paling dikhawatirkan Soeharto, saya kira memang Megawati. Karena Gus Dur sendiri dalam strategi politiknya waktu itu: zig-zag, kadang melawan, kadang mundur, kemudian negoisasi.
Gus Dur juga sempat menyarankan hal yang sama pada Megawati. Tujuan Gus Dur menghindari "kekerasan berdarah dari reaksi keras rejim" yang akan membuat kita "tidak dapat beranjak maju dalam mencapai cita-cita". Saran Gus Dur itu dikomentari oleh Greg Barton "Gus Dur memang benar, tetapi tidak sepenuhnya" (hal. 267).
Karena Soeharto tidak hanya puas menggusur Megawati dari kepemimpinan PDI. Orde Baru bertekad menodai reputasi Megawati dan menciptakan kecurigaan mengenai motif mereka yang mendukungnya. Dengan bekerja sama dengan sekutu-sekutunya di sayap kanan ICMI, jenderal-jenderal "hijau" Soeharto mulai menggunakan Muslim konservatif untuk menjelek-jelekkan Megawati dan "PRD Komunis" yang mendukungnya.
Dalam kondisi ini, Megawati tetap menampilkan keteguhan hati dan kesabaran revolusioner, seperti banteng yang tak kenal takut dan terus maju menyongsong amukan badai Orde Baru dan Soeharto.
Megawati-Gus Dur: "Cory Aquino-Kardinal Sin"
Soeharto bisa jadi jeri dengan pengalaman tumbangnya Ferdinand Marcos Diktator Filipina tahun 1986 yang berkuasa sejak 1965 melalui gerakan rakyat yang dipimpin oleh seorang perempuan: Corazon "Cory" Aquoino. Istri dari mendiang Benigno "Ninoy" Aquino, senator Filipina yang paling lantang menentang Ferdinand Marcos yang dibunuh pada tahun 1983.
Mudah ditebak Cory Aquino versi Indonesia adalah Megawati Soekarnoputri.
Bukankah Soeharto pula yang bisa dianggap paling bertanggung jawab "membunuh" pelan-pelan Bung Karno dalam status penghinaan yang luar biasa, kepada Proklamator Kemedekaan, Bapak Bangsa Indonesia dan Penyambung Lidah Rakyat sebagai "tahanan rumah" dalam tekanan psikis yang mahahebat hingga kesakitan fisik tapi tidak didukung dengan pengobatan dan perawatan yang memadai?
Bukankah penahanan dan penelantaran ini sama artinya dengan upaya pembunuhan pelan-pelan?
Masuknya Megawati ke PDI kemudian terpilih menjadi anggota DPR pada tahun 1987, hingga terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada tahun 1993 melambungkan kembali Soekarnoisme dalam politik. Sedangkan Soeharto melalui rejim Orde Baru tak henti-henti melakukan "desoekarnoisasi" termasuk pembunuhan fisik dan karakter.
Soeharto benar-benar melihat aura Cory Aquino yang menumbangkan Ferdinand Marcos pada sosok Megawati Soekarnoputri yang sedang mengancam kekuasaannya.
Bukan Gus Dur kalau tidak bisa membuat humor soal Megawati dan Cory Aquino yang digunakan sebagai perlawanan untuk meledek Soeharto dan Orde Baru.
Gus Dur suka bercerita mengenai rapat umum tahun 1995 yang dihadiri Jenderal Syarwan Hamid, juru bicara ABRI saat itu, Syarwan pernah berpidato "Saya sangat khawatir mengenai aliansi antara Gus Dur dan Megawati, hal ini tidak baik sama sekali bagi masyarakat karena akan merusak stabilitas dan bersifat merusak, mereka kira di Filipina, seolah-olah Megawati adalah Cory Aquino dan Gus Dur adalah Kardinal Sin--mereka kira mereka ini siapa!".
Gus Dur cepat menukas "Syarwan, jika Mbak Mega adalah Cory Aquino dan saya Kardinal Jaime Sin maka siapa yang menjadi Ferdinand Marcos?!"
Mendengar celetukan Gus Dur Syarwan langsung bangkit dan meninggalkan auditorium sementara para hadirin mulai berteriak bersama-sama: "Ya Wan, Wan, siapa yang menjadi Ferdinand Marcos, Wan!"
Secara tak langsung Syarwan Hamid mau menyamakan Soeharto dengan Ferdinand Marcos! Sama-sama diktator! Sama-sama berhadapan dengan seorang perempuan dan agamawan yang melawan!
Dan joke itu memang efektif untuk mendelegitimasi rejim Orde Baru dan semakin meneguhkan pasangan Megawati dan Gus Dur yang menjadi ancaman serius bagi Soeharto.
Gus Dur dan Megawati hanyalah dua tokoh dari kalangan intelektual, LSM dan partai politik yang muncul dan punya pengaruh besar terhadap gerakan oposisi pada Orde Baru, yang menurut Anders Uhlin dari sekian banyak kekuatan-kekuatan "oposisi berserak" yang memenuhi ruang-ruang perlawanan terhadap Orde Baru.
Ada gerakan mahasiswa, gerakan rakyat, LSM pro demokrasi, intelektual, partai politik, buruh dan lain-lainnya.
Karena itulah Tragedi 27 Juli 1996 harus dibaca dalam konteks politik saat itu, sebagai upaya cawe-cawe politik Soeharto paling brutal untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya dan yang paling utama adalah Megawati.
Kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh rejim Orde Baru ternyata menjadi bumerang bagi Soeharto. Sungguh tepat apabila Peter Kasenda dalam buku "Peristiwa 27 Juli 1996" yang menyebut Peristiwa itu sebagai "titik balik perlawanan rakyat".
Dan perlawanan itu ibarat kobaran api nan tak kunjung padam, menyalakan api perlawanan di mana-mana yang menjalar dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari satu kelompok ke kelompok yang lain, dari satu organ ke organ yang lain, sehingga semuanya mewarisi api perlawanan Peristiwa 27 Juli 1996 yang pada akhirnya mengobarkan Api Reformasi 1998 yang menumbangkan Soeharto.
Saya kira tidak berlebihan kalau Ribka Tjibtaning, Ketua DPP PDI Perjuangan, yang memiliki sejarah yang panjang sebagai aktivis oposisi terhadap Orde Baru dan Soeharto sekaligus pelaku sejarah gerakan-gerakan perlawanan termasuk Tragedi 27 Juli 1996 mengatakan bahwa Tragedi 27 Juli adalah tonggak reformasi.
"Tak ada Reformasi kalau tidak ada Kudatuli, kalau tidak ada Reformasi maka tidak ada tukang kayu jadi Presiden!"
Maksudnya: Jokowi tidak akan pernah bisa menjadi Presiden kalau tidak ada Reformasi, dan kalau tidak ada Peristiwa Kudatuli.
Karenanya Negara dalam hal ini Pemerintahan Jokowi harus mau mengakui Tragedi 27 Juli 1996 merupakan pelanggaran HAM berat.
Pada Peringatan 27 Juli tahun 2024 ini sudah terhitung 28 tahun para korban dan keluarga menuntut keadilan dari Negara.
Alam semesta sepertinya memberikan tanda: 27 Juli tahun 2024 ini juga bertepatan dengan hari Sabtu, hari yang sama dengan 27 Juli tahun 1996 "Sabtu Kelabu".
Ternyata tidak hanya persamaan hari (Sabtu) antara 27 Juli 1996 dan 27 Juli 2024 namun ada persamaan--yang menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto--"suasana kebatinan" terkait--ia mengutip istilah dari mantan aktivis gerakan reformasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) Wilson Obrigados--bangkitnya Neo Orde Baru "suasana kebatinannya yang semakin menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan tampaknya semakin menunjukkan kemiripan apa yang menjadi setting latar belakang peristiwa 27 Juli 1996 tersebut".
Wilson menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Kudatuli, Kami Tidak Lupa" di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2024 yang dalam pengakuannya datang kembali ke tempat kejadian 27 Juli 1996 selama hampir 28 tahun tapi masih merasakan kengerian akibat kejadian itu.
Jokowi: Soerjadi atau Soeharto?
Wilson menyamakan peristiwa Kudatuli 1996 dengan Peringatan Kudatuli 2024 dalam fenomena politik di era Presiden Jokowi
“Jadi Jokowi yang lahir dari PDI Perjuangan, karier politiknya dibesar oleh PDI Perjuangan, di masa-masa akhir jabatannya justru dia berkhianat terhadap PDI Perjuangan," kata Wilson.
"Dia ini (Jokowi) seperti Malin Kundang politik. Betul-betul sangat durhaka kepada ibu kandung politiknya sendiri. Dan kita tahu dalam dongeng Malin Kundang, dia berakhir menjadi batu,” lanjut Wilson.

Apakah Wilson menemukan sosok Soerjadi dalam sosok Jokowi?
Ternyata lebih jauh dari itu, Wilson membandingkan Jokowi dengan sosok Soeharto karena politik Orde Baru sedang dibangun oleh pemerintahan Jokowi sekarang.
Dia mencontohkan sejumlah peristiwa yang mengindikasikan kemunculan Neo Orba ini, seperti putusan MK yang menguntungkan Gibran putera sulung Jokowi dan putusan MA yang menguntungkan Kaesang putera bungsu Jokowi.
Wilson juga mengungkap kekhawatirannya atas pemerintahan Prabowo mendatang. Dia menganggap bahwa pemerintahan Prabowo akan tetap berada dalam bayang-bayang Jokowi yang sebelumnya telah banyak melakukan pelanggaran konstitusi.
"Rezim ke depan nanti akan mengabdi pada kekuasaan kelompok dan dinasti. Itu bahaya bagi demokrasi. Menurut saya itulah Orde Baru Jilid II," tegas Wilson.
Orde Baru sudah tumbang. Soeharto sudah jatuh, tapi apa lacur, roh-roh kesetanan kekuasaan Orde Baru kini merasuki penguasa-penguasa sekarang yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.
Karena itulah pengakuan Tragedi 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran HAM berat menjadi hal yang sangat mendesak.
Karena tidak hanya untuk menjawab tuntutan keadilan bagi korban, namun juga agar peristiwa brutal itu yang melibatkan ketamakan kekuasaan itu tidak berulang.
Satyam Eva Jayate. Kebenaran Pasti Menang!