Jakarta, Gesuri.id - Dalam tahun 1933, Bung Karno mengadakan perbedaan antara “azas”, “azas-perdjoangan”, dan “taktik”.
Menurutnya, “azas adalah dasar atau ‘pegangan’ kita, jang, ‘walau sampai lebur-kiamat’, terus menentukan ‘sikap’ kita, terus menentukan ‘duduknja njawa kita’.
Baca: Bung Karno, PDI Perjuangan Aceh Gelar WEBINAR Pada 17 Juni
Azas tidak boleh kita lepaskan, tidak boleh kita buang, walaupun kita sudah mentjapai Indonesia-Merdeka, bahkan malahan sesudah tertjapainja Indonesia-Merdeka itu harus mendjadi dasar tjaranya kita menjusun kita punja masjarakat.”
.
Familier dengan pengertian ini? Ya, sekilas tampak seperti Bung Karno berusaha memaparkan Pancasila sebagai dasar negara.
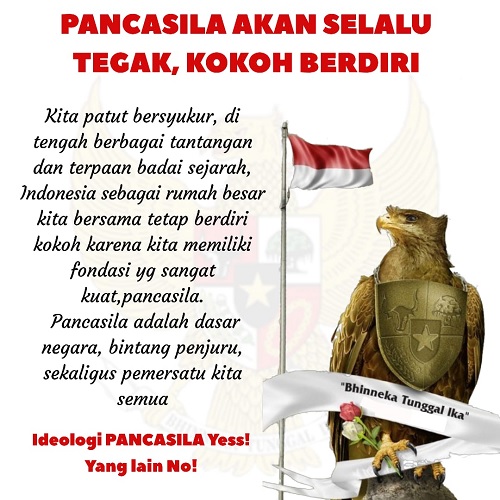
Namun, karangan ini terbit dalam Suluh Indonesia Muda pada tahun 1933, tercatat dalam Dibawah Bendera Revolusi Jilid I (Jakarta: Panitya Penerbit, 1965), dua belas tahun sebelum Radjiman Wedjodiningrat mengajukan persoalan dasar negara dalam sidang BPUPK. Apa yang dimaksudkan Bung Karno dengan asas kala itu?
.
“Bagi kita Marhaen Indonesia, azas kita ialah kebangsaan dan ke-Marhaen-an,—sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Bukan sekarang sahadja kita ‘memegang’ kepada sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi itu, tetapi sampai sesudah merdeka, sampai sesudah imperialisme-kapitalisme hilang, ja ‘sampai lebur-kiamat’ kita tetap berazas sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.”
.
Lantas, mengapa sesudah merdeka justru negara Indonesia berasaskan Pancasila? Apakah Bung Karno salah perhitungan?
Tidak juga. Apabila kita ingat, Bung Karno pernah menawarkan untuk memeras lima sila dalam Pancasila menjadi Trisila dalam pidato tanggal 1 Juni 1945—tanpa mengubah substansi yang dikandungnya. Trisila yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokasi, dan ketuhanan.
Baca: Bulan Bung Karno, PDI Perjuangan Nunukan Gelar Lomba Puisi
.
Artinya, jauh sebelum Bung Karno memaparkan di hadapan sidang BPUPK, beberapa tahun sebelum diasingkan di Ende, di mana ia seringkali duduk merenung di bawah sebatang pohon sukun, persoalan dasar negara rupa-rupanya sudah ia pikirkan matang-matang sejak awal 1930-an.
Soekarno menyebut pengasingan ke Ende membuatnya menjadi "seekor elang yang telah dipotong sayapnya". Pengasingan di Ende membuat Soekarno terguncang dan tidak berdaya secara politik.
Namun, alih-alih tempat pembuangan, Ende justru menjadi rumah pemulihan bagi Soekarno. Di Ende-lah Soekarno menemukan pribadinya yang paling dalam, berubah dari manusia "singa podium" menjadi "manusia perenung". (Sumber: @presidensukarno)








































































































